Manufacturing "Islam Lite": Sufism as "Good Islam"
The lecture hall was almost empty. A few loyal souls had shown up … But the vast majority of the seats were unclaimed. Esfandi had for some reason entitled his lecture ‘Fire and Surrender in the Islamic Way’, as if not remembering, or even caring, that Islam was hardly a popular subject around here [Santa Barbara, CA]. If he’d substituted the word ‘Sufi’, there’d have been blondes in the back row. - Pico Iyer
****
The affirmative denial “I am not religious but I am spiritual” that has achieved ubiquitous purchase in recent years crystallizes this logic of difference. The spiritual here refers to something ineffable that is not really religion but that owes its recognition precisely in relation to religion. Spirituality takes the form of secularized religion unencumbered from institutional, doctrinal, and ritual demands. The rebirth of religion as spirituality is made possible by the power of the secular imaginary within which religion represents something out there, always available for critique, moderation, and humanization. It is precisely such a secular notion of the spiritual that sustains the liberal demand for religious moderation, a demand that is made most frequently on Islam and Muslims today. - SharAli Tareen
Spiritual but Not Religious?
How many times have you heard the adage: “I am spiritual but not religious”? Perhaps you believe in this framing in describing your own approach to faith. But what does this sentence evoke? Is it an innocent, enlightened distancing from the confines of “organized” religion? You might not think much of it, but such framing drives the liberal bias towards “spirituality” as being a “good” category of practice as opposed to “bad” religion. It is a loaded proclamation. In SherAli Tareen’s words above, “spiritual but not religious” sustains a “secular notion of the spiritual that sustains the liberal demand for religious moderation, a demand that is made most frequently on Islam and Muslims.” While this phrase emerged from an era of critiquing organized religion and dogma—namely, that of Christianity— it primarily affects perceptions of Islam and Muslims.
Based on the logic of spiritual > religious, any Muslim who resists the status quo based on religious conviction—like the very religious communities in Gaza, Lebanon or Yemen—are immediately cast as suspect according to the liberal gaze. This framing provides fodder for imperial aims because it makes it more OK to exterminate “bad Muslims.”. Born out of the modernist, Protestant experience, the subjectivity of American and European views on religion in general and the perpetual “othering” of Islam, such rhetoric provides cover for the ongoing expansionist military policies towards Muslims abroad and the surveillance, incarceration and silencing of American Muslims domestically.
Think I am exaggerating? Allow me to elaborate. For this post, we will take a bit of a more academic deep dive behind the way Sufism has been manufactured as a “liberal”, “spiritual” (read: good) form of Islam and why that binary is dangerous and actually continues to feed genocidal policies against Muslim-majority communities.
In 1906, American spiritualist W.J. Colville wrote about the differences between “Mohammedans”; admitting that not all devotees of the Muslim faith are “narrow-minded or bigoted.” He highlighted that while “Sunees” are the least flexible in their interpretations of the Qur’an, the “Sheeah of Persia” are more enlightened and “elastic in their interpretations.” Like Orientalists before (and after him), Coleville would not be the first to tie Persian mysticism to a more favorable Western cosmopolitan approach to religion. Another Orientalist text on the Middle East refers to the “rigid monotheism of the Arab mind” compared to the flexibility of the mind of Persians and Indians.The Orientalist favoring of “Soofism” as less concerned with Islamic law and “Arab dogma” also viewed “mystics” as less likely to defy imperialist projects than other Muslim groups (which, if you’ve been following my work for sometime, is a huge falsehood, as Muslim Sufi scholars were once at the forefront of anti-colonial resistance.)
Rumi Watered Down
Perhaps one of the most popular American exposures to Sufism has come through the English-version poetry of the famous 13th-century scholar and jurist Jalaluddin Rumi, known simply as Rumi in the mainstream. Versions of Rumi’s poetry are the best-selling poetry books in America to date. Madonna sang versions of his poetry as adapted by guru Deepak Chopra. Donna Karan used recitations of his poetry as a background to her fashion shows. Directly after September 11th, The Soul of Rumi, 400-pages of poetry translated by Coleman Barks, made the best-sellers list. For an age-old Muslim poet hailing from modern-day Balkh, Rumi’s popularity in the mainstream typifies the American fetish towards Sufism. (Read “The Erasure of Islam from Rumi’s Poetry”, here).
On social media, this ad for “Rumi Spice” might pop up on your feed: which boasts itself as being “Michelin-quality spice from Afghanistan that supports Afghan women.” Rumi. Spice. Oppressed Women. Ah, nothing sells better than that sensationalist trifecta that continues to exoticize and dehumanize Muslim women who are in dire need of saving from savage brown men. Rumi’s American, consumerist fame is further sustained in the world of “feel good spirituality” accounts that feed collective narcissism in the garb of ancient wisdom, where quotable self-help quotes amidst the backdrop of pretty sunsets attributed to him circulate rather widely.
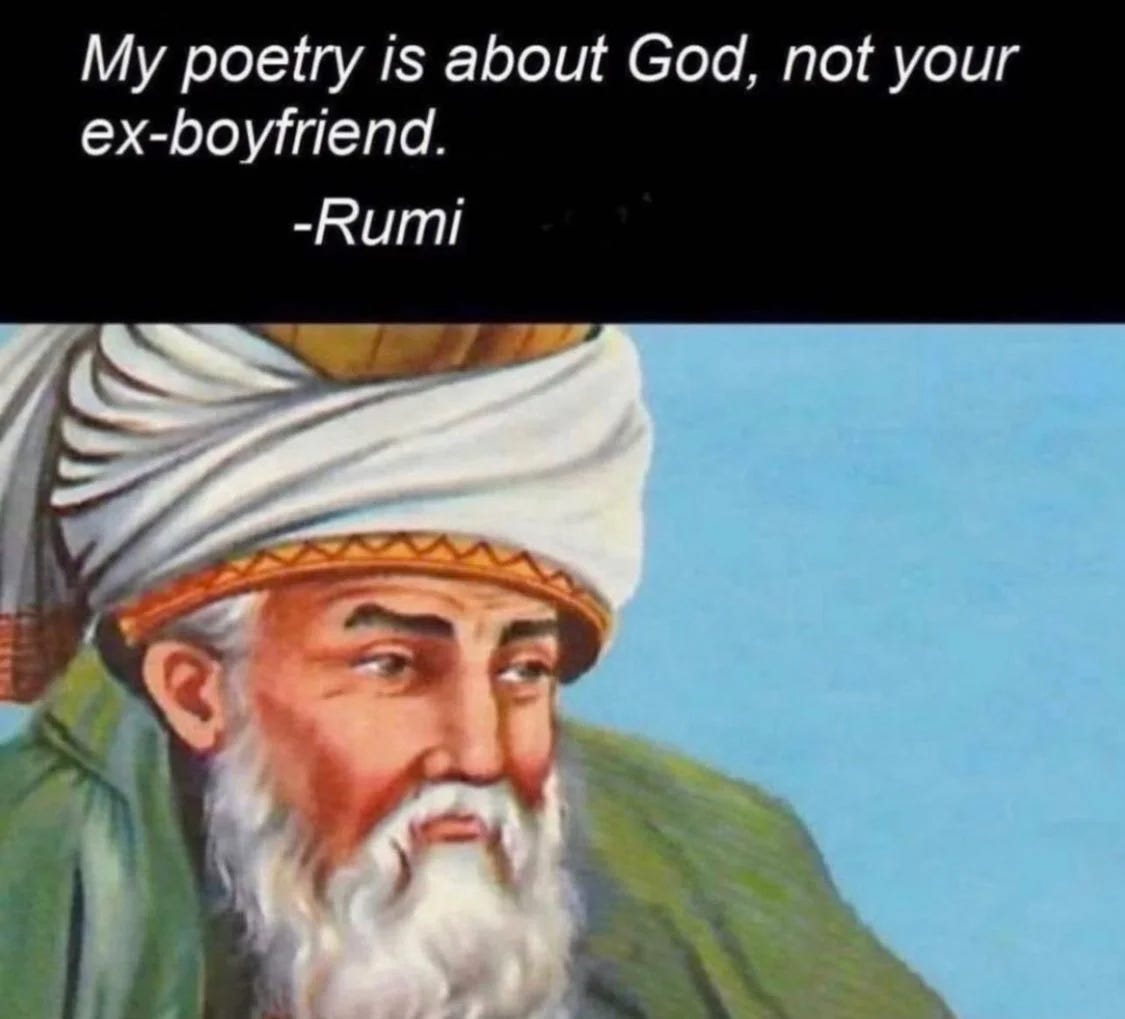
While some of the memes and quotes are more often accurate or are close translations to Rumi’s original work, most are not, which points to an active process of transforming a 13th-century Muslim jurist into a watered-down hippie New Age mystic. In an article that is no longer online, “Facebook Rumi: How a Muslim Mystic Became a Popular Meme,” Professor Omid Safi notes that the contemporary misappropriation of Rumi rests mainly on themes of “eroticism,” and on a “foolishness” that replaces real wisdom. The appetite for Rumi points to a hostility towards “organized religion”— even though “Rumi who taught in a madrasa himself.” (Safi)
Safi regards the modern-day “Social Media Rumi” phenomenon “as a sign of contemporary individualistic, feel-good consumerism that is interested in individual experience more than any type of spiritual transformation.” Safi and other Persianists and scholars of Sufsim, stress the need of situating Rumi back into the Islamic tradition where he belongs. Safi reminds us that Rumi was “profoundly connected to the Prophet,” reminding us that he saw himself the “offspring of the soul of Muhammad.” Indeed, even the Sufi order based on Rumi’s teachings, the Mevlevi order, has been romanticized in the West as “whirling dervishes”, when in fact, their teachings emphasize serious commitment, ritual, community, and discipline, values that are on the brink of extinction in most Western societies today.
But what does this ongoing fascination with Rumi the Persian Sufi tell us? Why is it relevant to our present moment?
Weaponizing Sufism
To answer this, let us go back about two decades. In a 2003 conference entitled “Understanding Sufism and its Potential Role in US Policy,” a right-wing DC think-tank, the Nixon Center, hosted a well-known Sufi scholar, Hesham Kabbani and Bernard Lewis, the prominent historian and scholar of the Middle East, who played an influential role in shaping Western policy toward the region, and whose scholarship is credited as being a driving force behind U.S.-led invasion of Iraq.
At the conference, he remarked: “But Sufism is remarkable, as it reflects something more than tolerance due to its universal nature.” Lewis references the poetry of Rumi and Ibn Arabi to commend Sufism’s superiority over “Islam proper” because it holds the idea “that all the religions are basically the same: all religions have the same purpose, the same message, the same communication, and they worship the same God”.
The demand of “sameness” that Lewis patronizingly expects of Muslims implies that Sufis are less likely to take critical political stances against Western imperial projects: read: they’re more like us, the good guys. But his words reveal something even more disingenuous: if the conference were truly about spirituality as an antidote to violence, then why didn’t it promote both Christians and Jewish expressions of mysticism as antidotal to “extremism”? Why would Kabbani, Lewis and the think-tank hawks that organized this conference place the entire onus on Islam to catch up to the superior universal standard of sameness enshrined in Christianity and Judaism? More importantly, according to Lewis’ favorable view of Sufis, since they are somehow “less Muslim,” (ie. better) it makes it more OK to exterminate those who are “fully Muslim.”
His co-host, Shaykh Kabbani reiterates Lewis’ understanding of Sufism as a universal equalizer. He begins his speech by also referencing Rumi and Ibn Arabi by citing their sayings:
I am a Muslim, but I don’t know if I am; I don’t know if I am a Christian or a Jew or an Austrian or an Eastern or a Western or an upper or lower. I don’t know if I am from the four elements of the world. I don’t know if I am from heaven or from earth. I don’t know if I am an Indian or a Chinese or a Bulgarian. I don’t know if I am Iraqi or Syrian. I don’t know if I am from Roroshan or Aswohan. I don’t know if I am from this world or that – but I am a body and a soul. My ego is my soul. When I mention two it means me and God.
Based on his interpretation of the above lines, Kabbani concludes that “Sufism works as a social power to bring people together” and assures his audience that “Sufis’ main goal was never to become the leaders of a country, but rather to become its social workers,” In performing for the Homeland Security personnel/think-tank hawk’s gaze, Kabbani ignores examples of numerous Muslim leaders in anti-colonial struggles such as Salahuddin Al-Ayyubi, Umar Futi Tal, Abdul Qādir Al-Jaza’eri, and Idris As-Senussi, who were all Sufis as well, but were involved in political rebellion and sometimes kingship/caliphate rule. (Kabbani also overlooks the legacies of scholarly warriors in his own spiritual lineage, the Naqshbandiyya, who, in Baghdad, formed a now-defunct army under the name of Jaysh Rijāl al-Tariqa al-Naqshbandiyya to combat the American invasion in Iraq, but I digress.)
Kabbani presents a selectively rosy picture of Sufism which has not always been as pacifist as he describes. Muslim informants such as Kabbani—and today, those who serve at the pleasure of the UAE government such as Abdullah Bin Bayyah, Hamza Yusuf and others—will readily rubber stamp a version of Islam that is malleable to the modernist, Protestant-based understanding of religion. A “good” pacifist, quietist, “cultural” Islam, as a opposed to a “bad,” Islam that resists oppression and state-tyranny. The irony is—rather than being docile, mild and meek—this form of quietest Islam is actually more politically radical than that of run-of-the-mill Islamists, because quietist Islam protects and promotes the extremist, fundamentalist policies enacted by nation states, their security apparatus and militaries. “Good Islam” hence provides ironclad theological cover for full blown state terrorism to be unleashed on innocent people. In thinking they support the Islamic ideals of civility and peace, they actually promote the anti-Islamic project of torture, debauchery and injustice.
The Union of Mysticism and Liberalism
It is important to locate the conflation of mysticism with moderation in the work nineteenth-century and twentieth-century scholars of Islamic studies at American universities. Scholars like Wilfred Cantwell Smith (d. 2000), Fazlur Rahman (d.1988), Seyyed Hossein Nasr (b.1933), H.A.R.Gibb (d.1971) and Annemarie Schimmel (d. 2003) would be the first to distinguish between Islamic practices deemed modern (legal debates, reform movements), and others seen as perennial (Sufism, metaphysics); transcending the test of time and thus are beyond compartmentalization into any one religion.
But even so, in a television interview on an Arabic-speaking channel with Professor Annemarie Schimmel, she was asked why “Westerners are so fascinated with Sufism,” to which she attributed the appeal of the theme of love: “they (Westerners) are interested [in Sufism] because they see in it the love for God as a central role and not so much the shari’ah” and added that this love for Sufism is actually misguided “because a good Sufi should follow shar’iah and all that it entails.” Schimmel here reflects a core teaching in the Islamic intellectual tradition, such as the saying by Imam Malik—the founder of Maliki legal school—who was known to have said: “Whoever studies tasawwuf (Sufism) without fiqh (jurisprudence) is a heretic, and whoever studies fiqh without tasawwuf is corrupted, and whoever studies tasawwuf and fiqh will find the truth and reality of Islam.” According to Imam Malik and Schimmel then, the obvious is stated: it’s not really Sufism if it’s not rooted in Islam.
In her paper, the Transformation of Indo-Persian “Mysticism” into Liberal Islamic Modernity, Corbett-Hicks suggests that the Cold War intersection of multi-national strategic interests and Orientalist knowledges birthed the “union of liberalisms and mysticisms.” Arguing against subjective narrative tropes, especially as they pertain to the study of Islam, Talal Asad suggests that scholars must investigate “the construction of specific historical narratives” around which their scholarship on religion is based. Asad presents us with useful tools for reading religion in new ways, especially when it comes to reading the liberal bias toward Sufism and the ways it gets manufactured and obscured in modernist, Protestant, Orientalist narratives.
To remedy this, we must cultivate an awareness that any discussion of Islam will ultimately be colored by a process of racialization. In her masterful work, The Invention of World Religions, Tomoko Masuzwa deals with the 19th century Orientalist view of Islam as a “Semitic” or Arab nationalist religion and how this perception would actually expel Islam outside the fold of world religions. This othering is why Islam it seen as backwards, belated and derivative from Jewish or Christian theologies. Masuzawa notes that representations of Islam as an Arab “invention” and a more rigid “byproduct” of Judaism, would help propel negative stereotypes against Muslims for centuries to come. In this pervasive climate of genocidal Islamophobia, I would say, boy, was she right.
Masuzawa cites the work of German Orientalist scholar Otto Pfleidere who sees Islam through a racialized lens; Islam as Arab, and Sufism as Arian:
A peculiarity of Persian Islamism, not less interesting, is Sufism, a mystical speculative tendency, some of which was deeply pious and given to flights of high thinking. Certain is that this was not a genuine product of Arabian Islamism, even though it must remain undecided whether it owes its origins to ancient Persian, Indian or Neo-platonic Gnosticism. (Pfleidere, p.202)
Masuzawa warns of the danger of representing Sufism in light of the “European imagination by the ethereal image of a ring of whirling dervishes in white,” pitted against the inherent rigid barbarism of “Islam proper.” Under the guise of nuance, by cherry-picking “positive” aspects of Islam, Orientalist scholars push for Islamophobia’s less-assuming twin, a type of Islamophilia. A project of manufacturing “good Islam” that still projects a sense of Western superiority over Muslims. When Sufism is divorced from the core of Islam, it implies that Sufism emerged despite Islam’s rigidity, not as an integral—organic—part of it.
The Orientalist fetishization of Sufism, then, appears to be advocating for something other than Islam altogether. Because, while laudatory accounts of Sufism may seem refreshingly positive, they are actually calling for a form of Islamic spirituality that is “more or less coeval with Christianity or, if not quite that, with something yet nameless but very much like Christianity of the future.” (Masuzawa, 204)
The Dangers of the “Good Muslim”
The essentialized categories of a more “mystical” or “Sufi” ie. “good,” version of Islam, pitted against a more “normative” and inept Islamic practice has massive—ultimately violent— implications: in Mahmood Mamdani's Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror, he critiques the binary framework that divides Muslims into "good Muslims" and "bad Muslims” for their egregious effects on foreign policy.
“Good Muslims” are those seen as “spiritual but not religious”, modern, secular, pro-Western, and politically compliant. They talk about women’s rights, they are proponents of non-violence, and they vote blue no matter who. “Bad Muslims” are framed as fundamentalists, extremists, or threats to Western ideals and security. Mamdani argues that this categorization has been used to justify political intervention and military action in Muslim-majority countries. Furthermore, this rhetoric reflects a colonial mindset, where compliance with Western interests (Sufism) is rewarded and dissent (Islam proper) is punished.
We’ve already read previously on this Substack who the main driver and primary beneficiary is behind the creation of the category of “Islamic Terrorism”: none other than the Benjamin Netanyahu, who has been trying to manufacture consent for ethnically cleansing, occupying and invading the Middle East since the 80s. With the destruction of Iraq, Afghanistan, Syria, Yemen, Sudan, Lebanon and Palestine well under way, one can very clearly see how lethal, poisonous and destructive the rhetoric of “good Muslim” “bad Muslim” can be. It can kill.
The project of manufacturing a neutered, aberration, liberal version of Islam single-handedly shapes and drives American foreign policy. The ongoing War-on-Terror/CVE/the Patriot Act/Muslim Ban/Abraham Accords sustains the campaign of mass violence towards Muslims. Both Democrats and Republicans push the same essentialist logic and strategies: by locating compliant “State Department types,” the “good” Muslim bedfellows who will readily serve as politically obedient partners (*ahem* pawns), Sufism becomes just one of many acceptable brands of a “watered down” Islam—a defanged, incomplete version of Islam—denying it the fullness of belonging a more holistic expression and deeper history.
While they are so ready to sell their soul for measly crumbs and “a seat the table,” Muslim native informants tend to forget that these efforts reveal two faces of the same coin: that Islamophilia towards one manufactured group of “good Muslims” is nothing more than Islamophobia towards all Muslims.
Today—with the Abraham Accords and other State Department efforts to “combat Islamism” with help of native informants and oppressive Muslim governments—the promotion of an aberrant, state-sponsored form of Islam in the form madkhaliSufism has been ensured. The hallmark identifiers of this Frankenstein Islam is accepting normalization with Israel and Great Power imperialism in the Muslim world.
With Trump back in power, prepare to see more efforts to “Promote Peace in Muslim Societies”, and initiatives towards a “less violent” more “civilized” form of Islam to be bolstered. I urge you to view these efforts for what they are: nothing but expendable tools in the pernicious game of colonial control. No matter how hard they try to justify it, informants who take part in such efforts do not realize that they are being played. Not only that, their collusion is deadly because as it hides under the fig leaf of “virtue”, “tradition” and “orthodoxy” to pit themselves against the politics of “modernists” “marxists” and “bad Islamists”—or any Muslim who resists state repression. By doing so, they thereby throw allMuslims under the colonialist bus and manufacture consent for genocide.
Whether post-9/11 or post-Oct. 7th, whether it is pushing for “Sufi Islam”, “Salafi Islam”, “Plain Vanilla Islam” or what have you, the problem lies in just that: the arrogant act of pushing, shaping and regulating Islam. What Orientalists, government officials and native informants cannot seem to fathom, that it is regulation and the desire to control Islam that is the source of tyranny and mass violence, not Islam or any version of it.
Any government efforts that try to quell so-called Muslim radicalization via a counterterrorism agenda through cozying to Sufis or any other group forgets that the desire to control Islam is much easier than the hard work of introspection. It is much harder to do the work of re-examining the core political issues and grievances that actually affect the lives of most Muslims worldwide: interventionist foreign policy and support for occupation, invasion, dehumanization, starvation, and mass killings of over 1 million Muslims and counting since 9/11.
Whether it is in the old-school “clash of civilizations” rhetoric in the likes of Colville who spoke about the differences between “Mohammedans”, “Sunees” and the “Sheeah of Persia” or Netanyahu, who justified Israel’s senseless ethnic cleansing campaign by warning Westerners that the “Judeo-Christian civilization is fighting for its life,” the obsession with regulating and pacifying Islam and Muslims has now reached its genocidal zenith.
The decades—if not centuries— of Orientalist fascination, exoticism, othering and demonization have come home to roost. Pitting any version of “good Islam” against a “bad Islam” has manufactured the rhetoric, logic and consent necessary to exterminate “bad Muslims”—who today in Gaza are babies, mothers, fathers—en masse.
It is time for those who, for so long, relied on the minstrel-esque act of performing the “good Muslim”—those who have enjoyed political expediency and upward mobility on the backs of their oppressed brothers and sisters—to repent and seek amends for their ways. It is also time for those who knowingly or unknowingly partake in manufacturing spirituality as a tool for colonial collusion—to take a good look at themselves. They might just find that—beneath the feel-good inter religious dialogue, the yoga lessons, the meditation retreats, the spirituality coaching—that their whole lifestyle has inadvertently manufactured consent for genocide.
Hicks, Rosemary R., Comparative Religion and the Cold War Transformation of Indo-Persian “Mysticism” into Liberal Islamic Modernity, Secularism and Religion-Making, ed. Dressler and Mandair, AAR, Oxford University Press, 2011, 141.
Dressler and Mandair, Secularism and Religion-Making, 149.
On Madkhalism: https://en.wikipedia.org/wiki/Madkhalism
TRANSLATE
Manufaktur "Islam Lite": Sufisme sebagai "Islam yang Baik"
Ruang kuliah hampir kosong. Beberapa jiwa yang setia telah muncul ... Tetapi sebagian besar kursi tidak diklaim. Esfandi untuk beberapa alasan memberi judul kuliahnya 'Api dan Menyerah dengan Cara Islam', seolah-olah tidak mengingat, atau bahkan peduli, bahwa Islam bukanlah subjek yang populer di sekitar sini [Santa Barbara, CA]. Jika dia mengganti kata 'Sufi', pasti ada pirang di barisan belakang. - Pico Iyer
****
Penyangkalan afirmatif "Saya tidak religius tetapi saya spiritual" yang telah mencapai pembelian di mana-mana dalam beberapa tahun terakhir mengkristalkan logika perbedaan ini. Spiritual di sini mengacu pada sesuatu yang tak terlukiskan yang sebenarnya bukan agama tetapi yang berutang pengakuannya secara tepat dalam kaitannya dengan agama. Spiritualitas mengambil bentuk agama sekuler yang tidak terbebani dari tuntutan institusional, doktrinal, dan ritual. Kelahiran kembali agama sebagai spiritualitas dimungkinkan oleh kekuatan imajiner sekuler di mana agama mewakili sesuatu di luar sana, selalu tersedia untuk kritik, moderasi, dan humanisasi. Justru gagasan sekuler tentang spiritual yang menopang permintaan liberal untuk moderasi agama, permintaan yang paling sering dibuat pada Islam dan Muslim saat ini. - SharAli Tareen
Spiritual tetapi Tidak Religius?
Berapa kali Anda mendengar pepatah: "Saya spiritual tetapi tidak religius"? Mungkin Anda percaya pada pembingkaian ini dalam menggambarkan pendekatan Anda sendiri terhadap iman. Tapi apa yang ditimbulkan oleh kalimat ini? Apakah itu jarak yang tidak bersalah dan tercerahkan dari batas-batas agama yang "terorganisir"? Anda mungkin tidak terlalu memikirkannya, tetapi pembingkaian seperti itu mendorong bias liberal terhadap "spiritualitas" sebagai kategori praktik "baik" yang bertentangan dengan agama "buruk". Ini adalah proklamasi yang dimuat. Dalam kata-kata SherAli Tareen di atas, "spiritual tetapi tidak religius" mempertahankan "gagasan sekuler tentang spiritual yang menopang permintaan liberal untuk moderasi agama, permintaan yang paling sering dibuat pada Islam dan Muslim." Sementara frasa ini muncul dari era mengkritik agama dan dogma yang terorganisir—yaitu, dari Kekristenan— itu terutama mempengaruhi persepsi Islam dan Muslim.
Berdasarkan logika spiritual > religius, setiap Muslim yang menolak status quo berdasarkan keyakinan agama—seperti komunitas religius di Gaza, Lebanon, atau Yaman—segera dilemparkan sebagai tersangka menurut tatapan liberal. Pembingkaian ini menyediakan makanan untuk tujuan kekaisaran karena itu membuatnya lebih baik untuk memusnahkan "Muslim yang jahat.". Lahir dari pengalaman modernis, Protestan, subjektivitas pandangan Amerika dan Eropa tentang agama secara umum dan "pendukung" Islam yang abadi, retorika semacam itu memberikan perlindungan bagi kebijakan militer ekspansionis yang sedang berlangsung terhadap Muslim di luar negeri dan pengawasan, penahanan, dan pembungkaman Muslim Amerika di dalam negeri.
Pikir saya melebih-lebihkan? Izinkan saya untuk menguraikan. Untuk postingan ini, kami akan mengambil sedikit lebih banyak penyelaman akademis di balik cara Sufisme telah diproduksi sebagai bentuk Islam yang "liberal", "spiritual" (baca: baik) dan mengapa biner itu berbahaya dan benar-benar terus memberi makan kebijakan genosida terhadap komunitas mayoritas Muslim.
Pada tahun 1906, spiritualis Amerika W.J. Colville menulis tentang perbedaan antara "Mohammedan"; mengakui bahwa tidak semua pemuja agama Muslim "berpikiran sempit atau fanatik." Dia menyoroti bahwa sementara "Sunees" adalah yang paling tidak fleksibel dalam interpretasi mereka terhadap Al-Qur'an, "Sheeah of Persia" lebih tercerahkan dan "elastis dalam interpretasi mereka." Seperti Orientalis sebelum (dan sesudahnya), Coleville tidak akan menjadi yang pertama untuk mengikat mistisisme Persia dengan pendekatan kosmopolitan Barat yang lebih menguntungkan terhadap agama. Teks Orientalis lainnya di Timur Tengah mengacu pada "monoteisme kaku dari pikiran Arab" dibandingkan dengan fleksibilitas pikiran Persia dan India. Orientalis yang menyukai "Soofisme" karena kurang peduli dengan hukum Islam dan "dogma Arab" juga memandang "mistikus" lebih kecil kemungkinannya untuk menentang proyek imperialis daripada kelompok Muslim lainnya (yang, jika Anda telah mengikuti pekerjaan saya untuk beberapa waktu, adalah kebohongan besar, karena ulama Muslim Sufi pernah berada di garis depan perlawanan anti-kolonial.)
Rumi Menjatuhkan Air
Mungkin salah satu paparan Amerika yang paling populer terhadap Sufisme berasal dari puisi versi bahasa Inggris dari sarjana dan ahli hukum abad ke-13 yang terkenal Jalaluddin Rumi, yang dikenal hanya sebagai Rumi di arus utama. Versi puisi Rumi adalah buku puisi terlaris di Amerika hingga saat ini. Madonna menyanyikan versi puisinya yang diadaptasi oleh guru Deepak Chopra. Donna Karan menggunakan pembacaan puisinya sebagai latar belakang untuk peragaan busananya. Tepat setelah 11 September, The Soul of Rumi, 400 halaman puisi yang diterjemahkan oleh Coleman Barks, masuk dalam daftar buku terlaris. Bagi seorang penyair Muslim kuno yang berasal dari Balkh zaman modern, popularitas Rumi di arus utama melambangkan jimat Amerika terhadap Sufisme. (Baca "Penghapusan Islam dari Puisi Rumi", di sini).
Di media sosial, iklan untuk "Rumi Spice" ini mungkin muncul di umpan Anda: yang membanggakan dirinya sebagai "Bumbu berkualitas Michelin dari Afghanistan yang mendukung wanita Afghanistan." Rumi. Bumbu. Wanita yang Tertindas. Ah, tidak ada yang menjual lebih baik daripada trifecta sensasional yang terus eksotis dan tidak manusiawi wanita Muslim yang sangat membutuhkan penyelamatan dari pria coklat buas. Ketenaran Rumi yang berasal dari Amerika dan konsumer semakin dipertahankan dalam dunia akun "merasa baik spiritualitas" yang memberi makan narsisme kolektif dalam pakaian kebijaksanaan kuno, di mana kutipan swadaya yang dapat dikutip di tengah latar belakang matahari terbenam yang indah yang dikaitkan dengannya beredar agak luas.
Sementara beberapa meme dan kutipan lebih sering akurat atau merupakan terjemahan yang dekat dengan karya asli Rumi, sebagian besar tidak, yang menunjukkan proses aktif untuk mengubah seorang ahli hukum Muslim abad ke-13 menjadi seorang mistikus Zaman Baru hippie yang encer. Dalam sebuah artikel yang tidak lagi online, "Facebook Rumi: Bagaimana seorang Mistik Muslim Menjadi Meme Populer," Profesor Omid Safi mencatat bahwa penyalahgunaan Rumi saat ini terutama bergantung pada tema "erotisisme," dan pada "kebodohan" yang menggantikan kebijaksanaan nyata. Nafsu untuk Rumi menunjukkan permusuhan terhadap "agama terorganisir"— meskipun "Rumi yang mengajar di madrasah sendiri." (Safi)
Safi menganggap fenomena "Media Sosial Rumi" zaman modern "sebagai tanda individualistik kontemporer, konsumerisme yang menyenangkan yang tertarik pada pengalaman individu lebih dari jenis transformasi spiritual apa pun." Safi dan Persia dan sarjana Sufsim lainnya, menekankan perlunya menempatkan Rumi kembali ke dalam tradisi Islam di mana dia berada. Safi mengingatkan kita bahwa Rumi "sangat terhubung dengan Nabi," mengingatkan kita bahwa dia melihat dirinya sebagai "keturunan jiwa Muhammad." Memang, bahkan tatanan Sufi yang didasarkan pada ajaran Rumi, tatanan Mevlevi, telah diromantiskan di Barat sebagai "derwis yang berputar", padahal pada kenyataannya, ajaran mereka menekankan komitmen serius, ritual, komunitas, dan disiplin, nilai-nilai yang berada di ambang kepunahan di sebagian besar masyarakat Barat saat ini.
Tapi apa yang dikatakan oleh daya tarik yang sedang berlangsung dengan Rumi sang Sufi Persia ini kepada kita? Mengapa itu relevan dengan momen kita saat ini?
Mempersenjatai Sufisme
Untuk menjawab ini, mari kita kembali sekitar dua dekade. Dalam konferensi tahun 2003 berjudul "Memahami Sufisme dan Peran Potensialnya dalam Kebijakan AS," sebuah think-tank DC sayap kanan, Nixon Center, menjadi tuan rumah bagi seorang sarjana Sufi terkenal, Hesham Kabbani dan Bernard Lewis, sejarawan dan sarjana terkemuka Timur Tengah, yang memainkan peran berpengaruh dalam membentuk kebijakan Barat terhadap wilayah tersebut, dan yang beasiswanya dikreditkan sebagai kekuatan pendorong di balik invasi Irak yang dipimpin AS.
Pada konferensi tersebut, dia berkomentar: "Tetapi Sufisme itu luar biasa, karena mencerminkan sesuatu yang lebih dari sekadar toleransi karena sifat universalnya." Lewis merujuk pada puisi Rumi dan Ibn Arabi untuk memuji keunggulan Sufisme atas "Islam yang tepat" karena memegang gagasan "bahwa semua agama pada dasarnya sama: semua agama memiliki tujuan yang sama, pesan yang sama, komunikasi yang sama, dan mereka menyembah Tuhan yang sama".
Permintaan "kesamaan" yang diharapkan Lewis dari Muslim menyiratkan bahwa Sufi cenderung tidak mengambil sikap politik kritis terhadap proyek kekaisaran Barat: baca: mereka lebih seperti kita, orang-orang baik. Tetapi kata-katanya mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih tidak jujur: jika konferensi itu benar-benar tentang spiritualitas sebagai penangkal kekerasan, lalu mengapa konferensi itu tidak mempromosikan ekspresi mistisisme Kristen dan Yahudi sebagai penangkal terhadap "ekstremisme"? Mengapa Kabbani, Lewis dan para think-tank hawks yang menyelenggarakan konferensi ini menempatkan seluruh tanas pada Islam untuk mengejar standar universal superior dari kesamaan yang diabadikan dalam Kekristenan dan Yudaisme? Lebih penting lagi, menurut pandangan Lewis yang menguntungkan tentang Sufi, karena mereka entah bagaimana "kurang Muslim," (yaitu lebih baik) itu membuatnya lebih baik untuk memusnahkan mereka yang "sepenuhnya Muslim."
Co-host-nya, Shaykh Kabbani menegaskan kembali pemahaman Lewis tentang Sufisme sebagai pemerataan universal. Dia memulai pidatonya dengan juga merujuk pada Rumi dan Ibn Arabi dengan mengutip ucapan mereka:
Saya seorang Muslim, tetapi saya tidak tahu apakah saya; Saya tidak tahu apakah saya seorang Kristen atau Yahudi atau Austria atau Timur atau Barat atau atas atau bawah. Saya tidak tahu apakah saya berasal dari empat elemen dunia. Saya tidak tahu apakah saya berasal dari surga atau dari bumi. Saya tidak tahu apakah saya orang India atau Cina atau Bulgaria. Saya tidak tahu apakah saya orang Irak atau Suriah. Saya tidak tahu apakah saya berasal dari Roroshan atau Aswohan. Saya tidak tahu apakah saya berasal dari dunia ini atau itu - tetapi saya adalah tubuh dan jiwa. Egoku adalah jiwaku. Ketika saya menyebutkan dua itu berarti saya dan Tuhan.
Berdasarkan interpretasinya terhadap kalimat di atas, Kabbani menyimpulkan bahwa "Sufisme bekerja sebagai kekuatan sosial untuk menyatukan orang" dan meyakinkan audiensnya bahwa "tujuan utama Sufi tidak pernah menjadi pemimpin suatu negara, melainkan menjadi pekerja sosialnya," Dalam tampil untuk tatapan personel Keamanan Dalam Negeri/think-tank hawk, Kabbani mengabaikan contoh banyak pemimpin Muslim dalam perjuangan anti-kolonial seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Umar Futi Tal, Abdul Qādir Al-Jaza'eri, dan Idris As-Senussi, yang semuanya juga Sufi, tetapi terlibat dalam pemberontakan politik dan terkadang pemerintahan kerajaan/kekekhalifahan. (Kabbani juga mengabaikan warisan prajurit ilmiah dalam garis keturunan spiritualnya sendiri, Naqshbandiyya, yang, di Baghdad, membentuk tentara yang sekarang sudah tidak berfungsi dengan nama Jaysh Rijāl al-Tariqa al-Naqshbandiyya untuk memerangi invasi Amerika di Irak, tetapi saya ngelantur.)
Kabbani menyajikan gambaran merah muda secara selektif dari Sufisme yang tidak selalu pasifis seperti yang dia gambarkan. Informan Muslim seperti Kabbani—dan hari ini, mereka yang melayani dengan senang hati pemerintah UEA seperti Abdullah Bin Bayyah, Hamza Yusuf dan lainnya—akan dengan mudah mendapatkan versi Islam yang mudah dibentuk oleh pemahaman agama berbasis Protestan dan modernis. Islam pasifis "baik", quietis, "budaya", sebagai lawan dari "buruk," Islam yang menolak penindasan dan tirani negara. Ironisnya adalah—daripada jinak, lembut, dan lemah lembut—bentuk Islam yang paling tenang ini sebenarnya lebih radikal secara politik daripada Islamis biasa, karena Islam yang tenang melindungi dan mempromosikan ekstremis, kebijakan fundamentalis yang diberlakukan oleh negara-negara bangsa, aparat keamanan dan militer mereka. "Islam yang Baik" karenanya memberikan perlindungan teologis yang kuat untuk terorisme negara penuh untuk dilepaskan pada orang-orang yang tidak bersalah. Dalam pemikiran mereka mendukung cita-cita Islam tentang kesopanan dan perdamaian, mereka sebenarnya mempromosikan proyek penyiksaan, pesta pora, dan ketidakadilan anti-Islam.
Persatuan Mistisisme dan Liberalisme
Penting untuk menemukan perbungaan mistisisme dengan moderasi dalam karya para sarjana abad kesembilan belas dan abad kedua puluh dari studi Islam di universitas-universitas Amerika. Sarjana seperti Wilfred Cantwell Smith (d. 2000), Fazlur Rahman (d.1988), Seyyed Hossein Nasr (b.1933), H.A.R.Gibb (d.1971) dan Annemarie Schimmel (d. 2003) akan menjadi yang pertama membedakan antara praktik Islam yang dianggap modern (debat hukum, gerakan reformasi), dan lainnya yang dipandang abadi (Sufisme, metafisika); melampaui ujian waktu dan dengan demikian melampaui kompartementalisasi ke dalam satu agama.
Namun demikian, dalam sebuah wawancara televisi di saluran berbahasa Arab dengan Profesor Annemarie Schimmel, dia ditanya mengapa "orang Barat begitu terpesona dengan Sufisme," yang dia kaitkan dengan daya tarik tema cinta: "mereka (orang Barat) tertarik [pada Sufisme] karena mereka melihat di dalamnya cinta kepada Tuhan sebagai peran sentral dan tidak begitu banyak syari'ah" dan menambahkan bahwa cinta untuk Sufisme ini sebenarnya salah arah "karena seorang Sufi yang baik harus mengikuti syariah dan semua yang diperlukannya." Schimmel di sini mencerminkan ajaran inti dalam tradisi intelektual Islam, seperti pepatah oleh Imam Malik—pendiri sekolah hukum Maliki—yang diketahui telah berkata: "Siapa pun yang mempelajari tasawwuf (Sufisme) tanpa fiqh (yurisprudensi) adalah bidat, dan siapa pun yang mempelajari fiqh tanpa tasawwuf adalah korup, dan siapa pun yang mempelajari tasawwuf dan fiqh akan menemukan kebenaran dan realitas Islam." Menurut Imam Malik dan Schimmel kemudian, yang jelas dinyatakan: itu tidak benar-benar Sufisme jika tidak berakar pada Islam.
Dalam makalahnya, Transformasi "Mistikisme" Indo-Persia menjadi Modernitas Islam Liberal, Corbett-Hicks menyarankan bahwa persimpangan Perang Dingin dari kepentingan strategis multi-nasional dan pengetahuan Orientalis melahirkan "persatuan liberalisme dan mistisisme." Berdebat menentang kiasan narasi subjektif, terutama yang berkaitan dengan studi Islam, Talal Asad menyarankan bahwa para sarjana harus menyelidiki "konstruksi narasi sejarah spesifik" yang menjadi dasar beasiswa mereka tentang agama. Asad memberi kita alat yang berguna untuk membaca agama dengan cara baru, terutama ketika datang untuk membaca bias liberal terhadap Sufisme dan cara-cara itu dibuat dan dikaburkan dalam narasi modernis, Protestan, Orientalis.
Untuk memperbaiki ini, kita harus menumbuhkan kesadaran bahwa setiap diskusi tentang Islam pada akhirnya akan diwarnai oleh proses rasialisasi. Dalam karyanya yang ahli, Penemuan Agama Dunia, Tomoko Masuzwa membahas pandangan Orientalis abad ke-19 tentang Islam sebagai agama nasionalis "Semit" atau Arab dan bagaimana persepsi ini benar-benar akan mengusir Islam di luar lipatan agama dunia. Hal lain inilah mengapa Islam dipandang terbelakang, terlambat dan diturunkan dari teologi Yahudi atau Kristen. Masuzawa mencatat bahwa representasi Islam sebagai "penemuan" Arab dan "produk sampingan" yang lebih kaku dari Yudaisme, akan membantu mendorong stereotip negatif terhadap Muslim selama berabad-abad yang akan datang. Dalam iklim Islamofobia genosida yang meluas ini, saya akan mengatakan, anak laki-laki, apakah dia benar.
Masuzawa mengutip karya sarjana Orientalis Jerman Otto Pfleidere yang melihat Islam melalui lensa rasial; Islam sebagai Arab, dan Sufisme sebagai Arian:
Keunikan Islamisme Persia, yang tidak kalah menarik, adalah Sufisme, kecenderungan spekulatif mistis, beberapa di antaranya sangat saleh dan diberikan pada penerbangan pemikiran yang tinggi. Yang pasti bahwa ini bukan produk asli dari Islamisme Arab, meskipun harus tetap belum diputuskan apakah asalnya berasal dari Gnostisisme Persia, India, atau Neo-platonis kuno. (Pfleidere, hal.202)
Masuzawa memperingatkan bahaya mewakili Sufisme dalam terang "imajinasi Eropa dengan gambar halus dari cincin derwis yang berputar-putar dalam warna putih," diadu dengan barbarisme kaku yang melekat dari "Islam yang tepat." Dengan kedok nuansa, dengan memilih aspek "positif" dari Islam, para sarjana Orientalis mendorong kembaran Islamofobia yang kurang berasumsi, jenis Islamofilia. Sebuah proyek pembuatan "Islam yang baik" yang masih memproyeksikan rasa superioritas Barat atas Muslim. Ketika Sufisme dipisahkan dari inti Islam, itu menyiratkan bahwa Sufisme muncul terlepas dari kekakuan Islam, bukan sebagai bagian integral—organik—darinya.
Fetishisasi Orientalis dari Sufisme, kemudian, tampaknya menganjurkan sesuatu selain Islam sama sekali. Karena, sementara catatan pujian Sufisme mungkin tampak positif yang menyegarkan, mereka sebenarnya menyerukan bentuk spiritualitas Islam yang "kurang lebih sejaat dengan Kekristenan atau, jika tidak cukup seperti itu, dengan sesuatu yang belum disebutkan namanya tetapi sangat mirip dengan Kekristenan di masa depan." (Masuzawa, 204)
Bahaya dari "Muslim yang Baik"
Kategori esensial dari versi Islam yang lebih "mistis" atau "Sufi" yaitu "baik,", diadu dengan praktik Islam yang lebih "normatif" dan tidak kompeten memiliki implikasi besar—pada dasarnya kekerasan: dalam Muslim Baik, Muslim Buruk: Amerika, Perang Dingin, dan Akar Teror karya Mahmood Mamdani, dia mengkritik kerangka kerja biner yang membagi Muslim menjadi "Muslim yang baik" dan "Muslim jahat" untuk efek mengerikan mereka pada kebijakan luar negeri.
"Muslim yang baik" adalah mereka yang dipandang sebagai "spiritual tetapi tidak religius", modern, sekuler, pro-Barat, dan patuh secara politis. Mereka berbicara tentang hak-hak perempuan, mereka adalah pendukung non-kekerasan, dan mereka memilih biru tidak peduli siapa. "Muslim jahat" dibingkai sebagai fundamentalis, ekstremis, atau ancaman terhadap cita-cita dan keamanan Barat. Mamdani berpendapat bahwa kategorisasi ini telah digunakan untuk membenarkan intervensi politik dan aksi militer di negara-negara mayoritas Muslim. Selain itu, retorika ini mencerminkan pola pikir kolonial, di mana kepatuhan terhadap kepentingan Barat (Sufisme) dihargai dan perbedaan pendapat (Islam yang tepat) dihukum.
Kami telah membaca sebelumnya di Substack ini siapa pendorong utama dan penerima utama di balik penciptaan kategori "Terorisme Islam": tidak lain adalah Benjamin Netanyahu, yang telah mencoba membuat persetujuan untuk pembersihan etnis, menduduki dan menginvasi Timur Tengah sejak tahun 80-an. Dengan penghancuran Irak, Afghanistan, Suriah, Yaman, Sudan, Lebanon, dan Palestina yang sedang berlangsung dengan baik, orang dapat dengan jelas melihat betapa mematikan, beracun, dan merusaknya retorika "Muslim baik" "Muslim jahat". Itu bisa membunuh.
Proyek pembuatan Islam versi Islam yang dikebiri, penyimpangan, dan liberal sendirian membentuk dan mendorong kebijakan luar negeri Amerika. Perang-Teror/CVE/Undang Patriot/Larangan Muslim/Perjanjian Abraham yang sedang berlangsung mempertahankan kampanye kekerasan massal terhadap Muslim. Baik Demokrat maupun Partai Republik mendorong logika dan strategi esensialis yang sama: dengan menemukan "tipe Departemen Luar Negeri yang patuh," teman-teman Muslim yang "baik" yang akan dengan mudah melayani sebagai mitra yang patuh secara politik (*ahem* pion), Sufisme hanya menjadi salah satu dari banyak merek yang dapat diterima dari Islam yang "dicairkan"—versi Islam yang tidak lengkap dan tidak lengkap—menyangkal kepenuhan milik ekspresi yang lebih holistik dan sejarah yang lebih dalam.
Sementara mereka sangat siap untuk menjual jiwa mereka untuk remah-remah yang sangat sederhana dan "duduk di meja," informan pribumi Muslim cenderung lupa bahwa upaya ini mengungkapkan dua wajah dari mata uang yang sama: bahwa Islamofilia terhadap satu kelompok buatan "Muslim yang baik" tidak lebih dari Islamofobia terhadap semua Muslim.
Hari ini—dengan Perjanjian Abraham dan upaya Departemen Luar Negeri lainnya untuk "memerangi Islamisme" dengan bantuan informan pribumi dan pemerintah Muslim yang menindas—promosi bentuk Islam yang menyimpang dan disponsori negara dalam bentuk Sufisme madkhali telah dipastikan. Pengidentifikasi ciri khas Islam Frankenstein ini adalah menerima normalisasi dengan Israel dan imperialisme Kekuatan Besar di dunia Muslim.
Dengan Trump kembali berkuasa, bersiaplah untuk melihat lebih banyak upaya untuk "Mempromosikan Perdamaian di Masyarakat Muslim", dan inisiatif menuju bentuk Islam yang "kurang kekerasan" lebih "beradab" untuk didukung. Saya mendorong Anda untuk melihat upaya-upaya ini apa adanya: tidak ada apa-apa selain alat yang dapat dibuang dalam permainan kontrol kolonial yang merusak. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk membenarkannya, informan yang mengambil bagian dalam upaya semacam itu tidak menyadari bahwa mereka sedang dipermainkan. Tidak hanya itu, kolusi mereka mematikan karena bersembunyi di bawah daun ara "kebajikan", "tradisi" dan "ortodoksi" untuk mengadu diri mereka melawan politik "modernis" "Marxis" dan "Islamis jahat"—atau Muslim mana pun yang menolak represi negara. Dengan melakukan itu, mereka dengan demikian membuang semua Muslim di bawah bus kolonialis dan membuat persetujuan untuk genosida.
Baik pasca-9/11 atau pasca-Oktober 7, apakah itu mendorong "Islam Sufi", "Islam Salafi", "Islam Vanila Polos" atau apa yang Anda miliki, masalahnya terletak pada hal itu: tindakan arogan dalam mendorong, membentuk, dan mengatur Islam. Apa yang Orientalis, pejabat pemerintah dan informan pribumi tampaknya tidak dapat dipahami, bahwa itu adalah peraturan dan keinginan untuk mengendalikan Islam yang merupakan sumber tirani dan kekerasan massal, bukan Islam atau versi apa pun darinya.
Setiap upaya pemerintah yang mencoba untuk memadamkan apa yang disebut radikalisasi Muslim melalui agenda kontraterorisme melalui kenyamanan dengan Sufi atau kelompok lain lupa bahwa keinginan untuk mengendalikan Islam jauh lebih mudah daripada kerja keras introspeksi. Jauh lebih sulit untuk melakukan pekerjaan memeriksa kembali masalah politik inti dan keluhan yang benar-benar mempengaruhi kehidupan sebagian besar Muslim di seluruh dunia: kebijakan luar negeri intervensionis dan dukungan untuk pendudukan, invasi, dehumanisasi, kelaparan, dan pembunuhan massal lebih dari 1 juta Muslim dan terus bertambah sejak 9/11.
Entah itu dalam retorika "bentrokan peradaban" jadul seperti Colville yang berbicara tentang perbedaan antara "Mohammedans", "Sunees" dan "Sheeah of Persia" atau Netanyahu, yang membenarkan kampanye pembersihan etnis Israel yang tidak masuk akal dengan memperingatkan orang Barat bahwa "peradaban Yahudi-Kristen berjuang untuk hidupnya," obsesi dengan mengatur dan menenangkan Islam dan Muslim sekarang telah mencapai puncak genosidanya.
Beberapa dekade—jika bukan berabad-abad— daya tarik Orientalis, eksotisme, perbedaan dan demonisasi telah datang ke rumah untuk bertengger. Mengadu versi apa pun dari "Islam yang baik" melawan "Islam yang buruk" telah menghasilkan retorika, logika, dan persetujuan yang diperlukan untuk memusnahkan "Muslim yang buruk"—yang saat ini di Gaza adalah bayi, ibu, ayah—dalam massa.
Sudah waktunya bagi mereka yang, begitu lama, mengandalkan tindakan minstrel-esque untuk melakukan "Muslim yang baik"—mereka yang telah menikmati kemanfaatan politik dan mobilitas ke atas di punggung saudara dan saudari mereka yang tertindas—untuk bertobat dan mencari perbaikan untuk jalan mereka. Ini juga merupakan waktu bagi mereka yang secara sadar atau tidak sadar mengambil bagian dalam pembuatan spiritualitas sebagai alat untuk kolusi kolonial—untuk melihat diri mereka sendiri dengan baik. Mereka mungkin hanya menemukan bahwa—di bawah dialog antar agama yang terasa baik, pelajaran yoga, retret meditasi, pelatihan spiritualitas—bahwa seluruh gaya hidup mereka secara tidak sengaja menghasilkan persetujuan untuk genosida.
1
Hicks, Rosemary R., Perbandingan Agama dan Transformasi Perang Dingin dari "Mistikisme" Indo-Persia menjadi Modernitas Islam Liberal, Sekularisme dan Pembuatan Agama, ed. Dressler dan Mandair, AAR, Oxford University Press, 2011, 141.
2
Baca proses konferensi, di sini.
3
Dressler dan Mandair, Sekularisme dan Pembuatan Agama, 149.
4
Tentang Madkhalism: https://en.wikipedia.org/wiki/Madkhalism


No comments:
Post a Comment